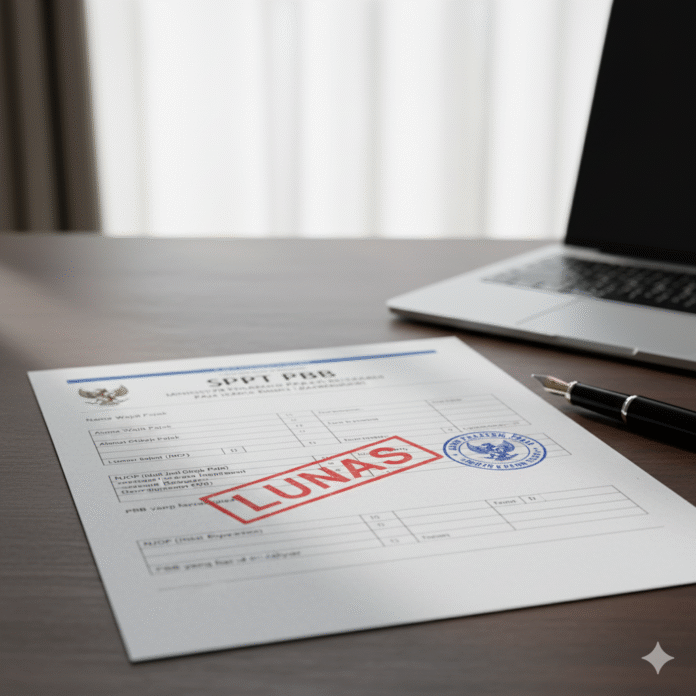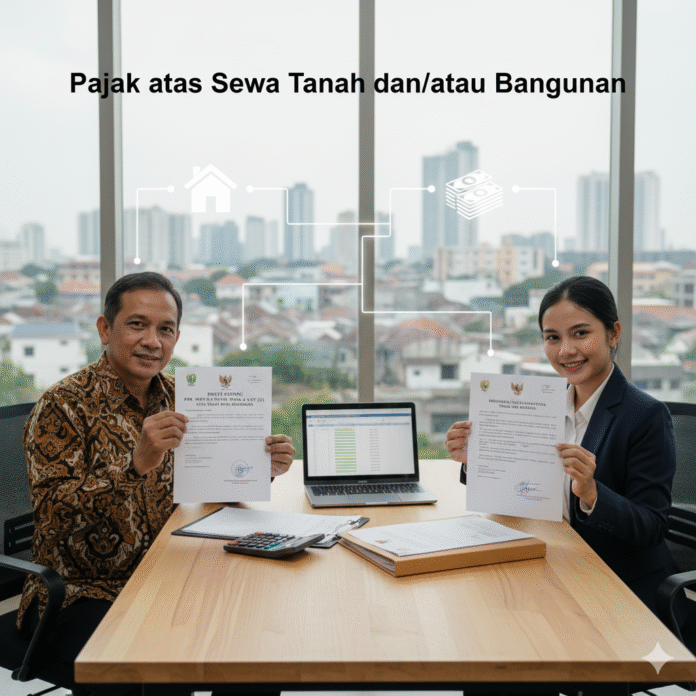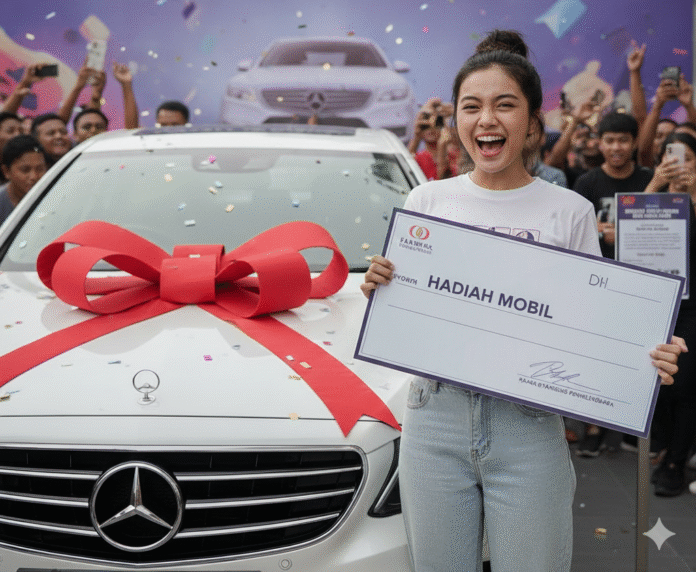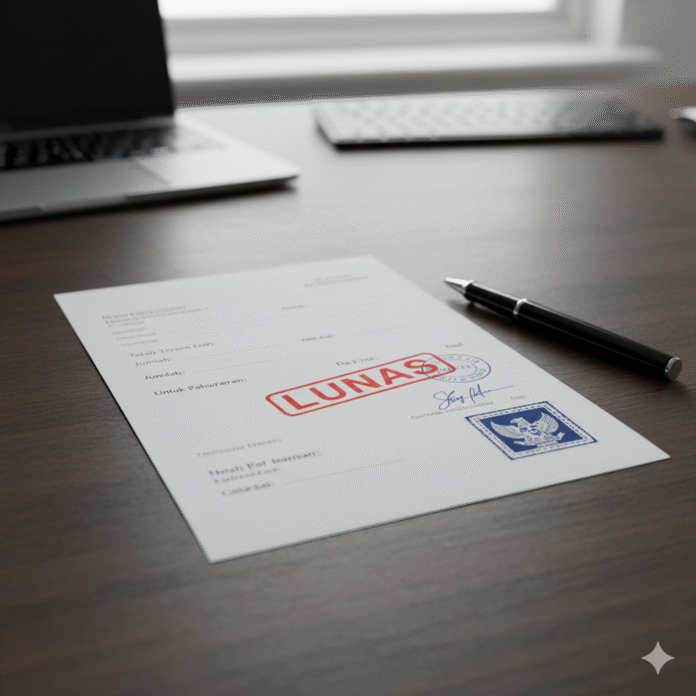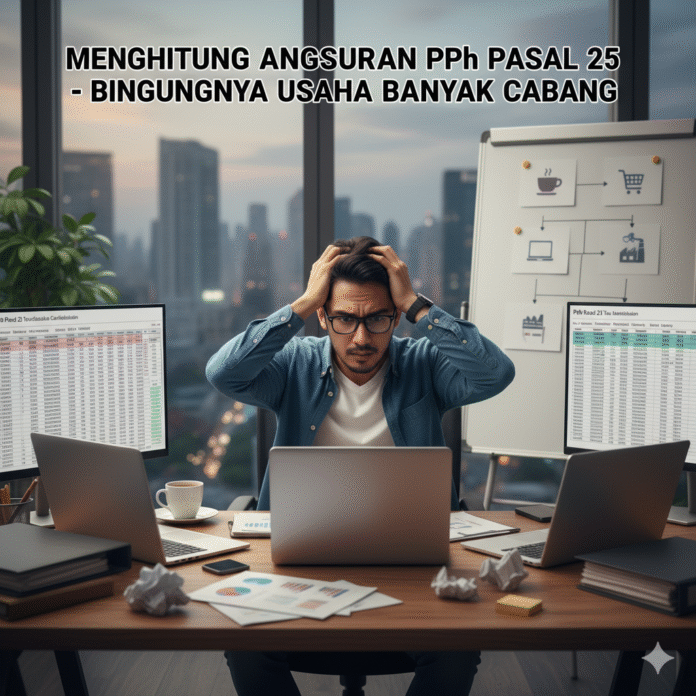Bayangkan Anda seorang pengusaha yang baru saja membeli gedung kantor. Harga sudah disepakati, kontrak ditandatangani, namun muncul pertanyaan: “Berapa nilai sebenarnya gedung ini untuk tujuan perpajakan?”
Di sinilah peran penilaian untuk tujuan perpajakan hadir. Proses ini bukan sekadar formalitas, tapi merupakan fondasi penting dalam menentukan kewajiban pajak yang adil, baik bagi wajib pajak maupun negara.
Artikel ini akan membahas tuntas mengenai penilaian untuk tujuan perpajakan, dasar hukum, lingkup, metode, hingga contoh penerapannya berdasarkan PMK No. 79 Tahun 2023.
Apa Itu Penilaian untuk Tujuan Perpajakan?
Secara sederhana, penilaian untuk tujuan perpajakan adalah proses menentukan nilai suatu objek (harta berwujud, tidak berwujud, maupun bisnis) yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.
Proses ini dilakukan oleh Penilai Pajak, yaitu pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab khusus dalam menilai objek pajakpenilaian untuk tujuan perpajak….
Dasar Hukum Penilaian untuk Tujuan Perpajakan
Beberapa regulasi penting yang menjadi landasan:
- UUD 1945 Pasal 17 ayat (3)
- UU KUP (UU No. 6 Tahun 1983, terakhir diubah UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP)
- UU PPh, UU PPN, UU PBB, dan UU PPSP
- PMK No. 186/PMK.03/2019 jo. PMK No. 234/PMK.03/2022 tentang klasifikasi objek pajak dan tata cara penetapan NJOP.
- PMK No. 79 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian untuk Tujuan Perpajakan (berlaku sejak 22 Agustus 2023).
Dengan regulasi ini, penilaian memiliki kepastian hukum dan standar baku dalam pelaksanaannya.
Jenis Penilaian dalam Perpajakan
1. Penilaian untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Dilakukan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- Bisa dilakukan melalui Penilaian Kantor (analisis data) atau Penilaian Lapangan (kunjungan langsung).
- Hasilnya digunakan dalam SPPT PBB, SKP, keberatan, hingga penyidikan kasus perpajakan.
2. Penilaian untuk Nilai Harta dan Bisnis
- Meliputi harta berwujud (tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, barang seni, aset biologis).
- Harta tidak berwujud (merek dagang, kontrak, teknologi, goodwill, lisensi).
- Bisnis (entitas baru, penyertaan saham, instrumen keuangan, laporan keuangan).
Metode Penilaian
Penilaian dilakukan dengan pendekatan yang berbeda sesuai objeknyapenilaian untuk tujuan perpajak…:
- Pendekatan Pasar → membandingkan dengan objek sejenis di pasar.
- Metode: pembanding data pasar, faktor pengali harga.
- Pendekatan Pendapatan → menghitung manfaat ekonomi atau pendapatan di masa depan.
- Metode: diskonto arus kas (DCF), kapitalisasi pendapatan, pengganda pendapatan kotor.
- Pendekatan Biaya → menghitung biaya reproduksi/penggantian dikurangi penyusutan.
- Pendekatan Aset (untuk bisnis) → menilai aset dan kewajiban perusahaan berdasarkan nilai pasar.
Hasil akhir berupa Laporan Penilaian, yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang.
Proses Penilaian: Dari Data hingga Laporan
- Penyiapan Bahan → pengumpulan dokumen, program, dan sarana.
- Pengumpulan Data → dari wajib pajak, pihak ketiga, atau data DJP.
- Analisis Data → melihat kondisi pasar, industri, laporan keuangan.
- Penerapan Pendekatan → pasar, pendapatan, biaya, atau aset.
- Penyusunan Laporan Penilaian → disusun oleh tim penilai dalam waktu maksimal 3 bulan sejak surat perintah dikeluarkan.
Kenapa Penilaian Ini Penting?
- Bagi Wajib Pajak: memastikan pajak yang dibayar sesuai dengan nilai sebenarnya, bukan perkiraan sepihak.
- Bagi Pemerintah: menjamin penerimaan negara tidak berkurang akibat undervaluation.
- Bagi Investor/Perusahaan: memberi kepastian nilai aset dan kewajaran transaksi (terutama untuk merger, akuisisi, atau transfer pricing).
Contoh Kasus Sederhana
Misalnya, sebuah perusahaan teknologi di Jakarta melakukan merger. Untuk menghitung kewajaran transaksi, DJP melakukan penilaian atas:
- Aset berwujud: gedung kantor, server, dan kendaraan operasional.
- Aset tidak berwujud: lisensi perangkat lunak, merek dagang, dan goodwill.
- Bisnis: nilai entitas secara keseluruhan berdasarkan laporan keuangan.
Dengan penilaian ini, pemerintah bisa memastikan bahwa nilai transaksi sesuai harga pasar, dan pajak yang timbul dihitung dengan adil.
Kesimpulan
Penilaian untuk tujuan perpajakan adalah jembatan antara wajib pajak dan negara dalam menentukan nilai yang adil. Dengan dasar hukum kuat dan metode profesional, penilaian ini memastikan kepastian hukum, transparansi, dan keadilan perpajakan.
Sebagai wajib pajak, memahami proses ini penting agar tidak hanya patuh, tetapi juga cerdas dalam mengelola kewajiban pajak.