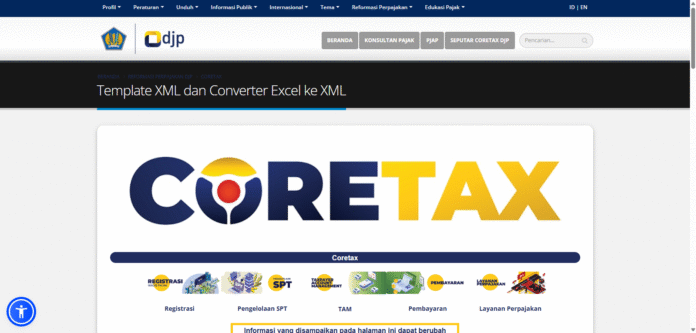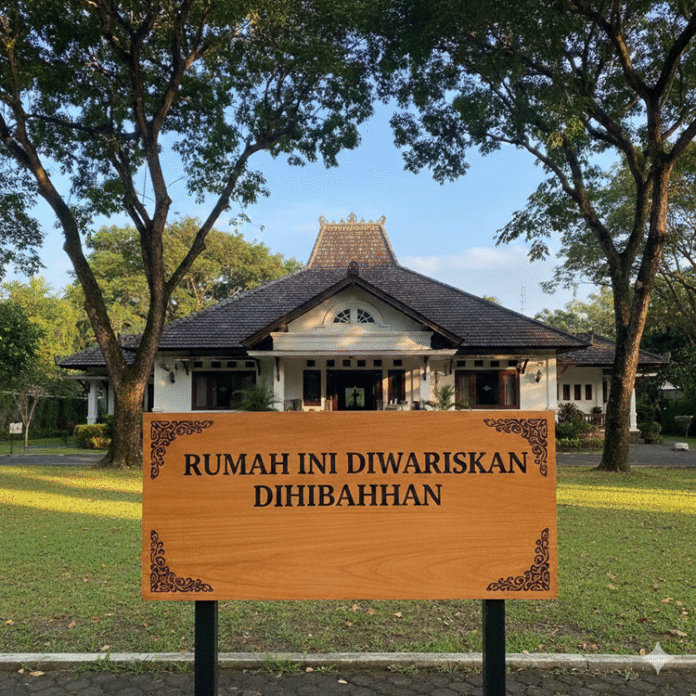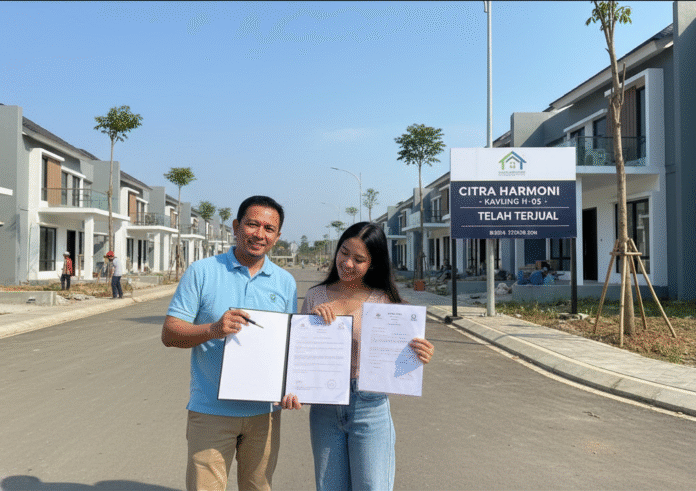Kalau Anda memiliki rumah, tanah kosong, atau ruko di kota maupun desa, pasti tidak asing lagi dengan istilah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Salah satu jenis PBB yang paling dekat dengan masyarakat adalah PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
PBB-P2 merupakan pajak daerah yang setiap tahunnya harus dibayar oleh pemilik atau pihak yang memanfaatkan tanah dan bangunan. Pajak ini hasilnya masuk ke kas daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan lokal, seperti perbaikan jalan, penerangan jalan, hingga fasilitas umum di sekitar kita.
Apa Itu PBB-P2?
Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan yang berada di wilayah perdesaan dan perkotaan.
👉 Sederhananya, kalau Anda punya tanah atau bangunan di kota maupun desa, Anda wajib bayar PBB-P2 setiap tahun.
Dasar Hukum PBB-P2
- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan daerah (Perda) di masing-masing kabupaten/kota yang mengatur tarif, NPOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak), dan tata cara pembayaran.
Siapa yang Wajib Bayar PBB-P2?
Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau memanfaatkan:
- Bumi → tanah, sawah, kebun, tanah kosong.
- Bangunan → rumah tinggal, apartemen, ruko, gedung perkantoran, gudang, pusat perbelanjaan, dll.
👉 Contoh:
- Pak Budi punya rumah di Jakarta → wajib bayar PBB-P2.
- Bu Sari punya tanah kosong di desa → wajib bayar PBB-P2.
Objek Pajak PBB-P2
Objek yang dikenakan PBB-P2 adalah bumi dan bangunan dengan kriteria:
- Bumi → permukaan tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
- Bangunan → konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah/perairan.
Termasuk bangunan: rumah, gedung, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, lapangan tenis, dermaga, taman mewah, dan lain-lain.
Cara Menghitung PBB-P2
Penghitungan PBB-P2 menggunakan formula berikut:
PBB Terutang = Tarif × (NJOP – NJOPTKP)
Keterangan:
- NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) → nilai jual tanah/bangunan ditetapkan pemerintah daerah.
- NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) → jumlah tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak (minimal Rp10 juta, tergantung daerah).
- Tarif PBB-P2 → maksimal 0,3% dari NJKP (Nilai Jual Kena Pajak).
Contoh Perhitungan
Misalnya, sebuah rumah di kota A punya NJOP Rp500.000.000, dan NJOPTKP daerah tersebut Rp15.000.000. Tarif PBB ditetapkan 0,1%.
PBB terutang:
= 0,1% × (Rp500.000.000 – Rp15.000.000)
= 0,1% × Rp485.000.000
= Rp485.000
👉 Jadi, pemilik rumah wajib membayar PBB sebesar Rp485 ribu per tahun.
Cara Membayar PBB-P2
- Terima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dari Pemda.
- Bayar di tempat yang ditunjuk, misalnya:
- Bank daerah, kantor pos, atau loket pembayaran.
- Aplikasi online/sistem e-BPHTB atau e-PBB (di beberapa daerah sudah tersedia).
- Simpan bukti pembayaran untuk arsip.
Manfaat Membayar PBB-P2
Banyak orang menganggap PBB hanya beban tambahan, padahal manfaatnya kembali ke masyarakat:
- Untuk pembangunan infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan, dan drainase.
- Untuk pelayanan publik seperti sekolah, puskesmas, dan penerangan jalan.
- Sebagai bukti kepatuhan, karena bukti pembayaran PBB sering diminta saat mengurus jual beli tanah atau bangunan.
Risiko Jika Tidak Bayar PBB-P2
- Denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari nilai PBB terutang.
- Penagihan aktif oleh Pemda jika menunggak lebih dari 1 tahun.
- Penyitaan atau lelang aset dalam kasus tertentu jika tidak ada penyelesaian.
- Kesulitan administrasi saat jual beli tanah/bangunan, karena bukti pembayaran PBB adalah salah satu syarat balik nama.
Perbedaan PBB-P2 dengan PBB Sektor Lain
- PBB-P2 → untuk tanah/bangunan di desa/kota, dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
- PBB-P3 (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan) → untuk sektor khusus, masih dikelola pemerintah pusat.
👉 Jadi, rumah pribadi, ruko, tanah kosong → masuk PBB-P2. Tapi perkebunan sawit besar atau tambang batu bara → masuk PBB-P3.
Tips Membayar PBB-P2 Tepat Waktu
- Tandai jatuh tempo di kalender Anda.
- Manfaatkan layanan pembayaran online jika daerah sudah mendukung.
- Bayar lebih awal untuk menghindari antrean panjang menjelang jatuh tempo.
Kesimpulan
PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak daerah yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas kepemilikan maupun pemanfaatan bumi dan bangunan di wilayah desa maupun kota.
- Pemungut: Pemerintah kabupaten/kota.
- Tarif: maksimal 0,3% dari NJKP.
- Manfaat: hasilnya digunakan untuk pembangunan daerah dan pelayanan publik.
- Risiko: jika tidak dibayar, terkena denda 2% per bulan hingga penagihan aktif.
👉 Jadi, jangan anggap remeh PBB-P2. Mungkin jumlahnya terlihat kecil, tapi manfaatnya besar untuk membangun daerah kita sendiri. Dengan membayar PBB tepat waktu, kita ikut berkontribusi langsung dalam pembangunan lingkungan sekitar.